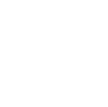Menyongsong Kopdarnas Penggiat Literasi: MENUMBUHKAN BUDAYA LITERASI
Dibaca: 1474
Penulis : Heru Prasetya

Tidak mudah menumbuhkan budaya baca. Tantangan datang dari segala penjuru, bisa diri sendiri, orang lain, situasi sosial, maupun ketersediaan fasilitas. Justru disitulah asyiknya. Niat dan semangat adalah faktor penentu keberhasilan, tetapi faktor lain tak kalah pentingnya. Sehingga hanya bermodal niat dan semangat, masih jauh panggang dari pada api untuk bisa disebut berhasil.
Penulis mengalami sejak 1987-an, atau 30 tahun lalu. Ketika itu masih tinggal di sebuah kampung wilayah Kota Yogyakarta. Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) di sana, gabungan Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul ‘Aisyiyah, memiliki program perpustakaan bernama Taman Pustaka. Tidak hanya niat dan semangat, kami punya ruang (pinjam garasi di rumah salah satu tokoh setempat), koleksi buku, dana, dan punya orang untuk mengelola.
Secara rasionalitas manusia, semua tinggal jalan. Apalagi kampung itu termasuk wilayah perkotaan (meskipun pinggiran) dengan tingkat pendidikan warganya lumayan tinggi. Mestinya tingkat kebutuhan membaca juga tinggi.
Memang di awal-awal buka, pengunjung termasuk banyak. Untuk sebuah garasi bermuatan satu mobil, dikunjungi 10 orang dalam satu waktu, sudah terasa sesak. Ada yang sekadar membaca di tempat, ada juga yang pinjam untuk dibawa pulang. Sirkulasi meminjam dan mengembalikan berjalan tertib.
Entah mengapa pada kira-kira bulan keempat, terjadi perubahan drastis. Jumlah pengunjung tidak seperti hari-hari sebelumnya, bahkan kadang ada hari tanpa satu pengunjung pun. Jemput bola ke jamaah (masyarakat) tidak membuahkan hasil. Jawabnya hanya “ya, ya, ya” tapi tak kunjung datang di Taman Pustaka kami. Menambah koleksi buku juga tak berdaya mengajak mereka hadir lagi di perpustakaan. Akhirnya, setelah melalui berbagai upaya dan evaluasi, kami seakan menjemput “takdir” bernama LIBUR PANJANG alias TUTUP.
Itu bukan pengalaman pertama. Sekarang, di tempat tinggal yang tidak lagi wilayah perkotaan, niatan membuka perpustakaan kembali muncul. Tujuannya tak lain adalah menumbuhkan budaya membaca. Karena dari situlah kecerdasan bisa dibangun.
Seiring dengan pertambahan umur, penulis lebih mengambil peran memberi ide kepada generasi muda melalui remaja masjid. Niat ada, semangat ada, ruang ada, almari ada, koleksi buku juga ada, dana ada. Kurang apalagi? Masyarakat juga ada. Sepertinya sudah ketemu antara pembaca dan yang dibaca. Tapi sampai 15 tahunan semua bisa dikata jalan di tempat. Buku-buku yang tadinya baru, mulai terlihat lusuh. Ruangan yang bersebelahan dengan masjid lebih banyak kosong, sepi, tanpa aktivitas.
Perbedaan waktu 30 tahun ternyata belum mampu mengubah masyarakat untuk masuk ke wilayah minat baca, perlu membaca, butuh membaca. Padahal kata pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT melalui Malaikat Jibril adalah “Iqro’…” Bacalah. Jelas dan tegas. Tanpa tafsir apapun, kata “bacalah” adalah perintah untuk membaca. Perintah dari Sang Maha Kuasa di bumi dan langit.
Tak bisa dibantah bahwa Islam adalah agama ilmu pengetahuan. Jauh sebelum kata “Iqro’…” diwahyukan kepada Rasulullah SAW, Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah fil ardh, pemimpin di muka bumi. Kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain adalah pada akal. Manusia diberi akal, makhluk lain tidak. Dengan akal inilah manusia memiliki couricity atau rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Klop, antara maksud Allah menciptakan manusia dengan Iqro’. Karena diberi akal, sehingga diperintahkan membaca. Sehingga membaca adalah sunnatullah.
Dua contoh kasus yang penulis alami di atas merupakan bukti bahwa persoalan budaya baca adalah masalah serius di negeri ini, termasuk umat Islam sebagai jumlah mayoritas. Penanganannya tidak bisa parsial, sepotong-potong. Seperti juga dalam kita ber-Islam, penanganan masalah literasi harus kaaffah, menyeluruh, dari hulu ke hilir dan sebaliknya.
Hal pertama dan utama yang harus dilakukan adalah melihat kembali alias mengevaluasi model kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan formal kita, dari TK (bahkan playgroup) hingga SMA/SMK/MA dan yang sederajat. Bukankah selama ini pelajar atau peserta didik lebih banyak “dijejali” kata yang keluar dari (maaf) mulut guru. Guru aktif, sedangkan murid tenang-tenang saja duduk di kursi, mungkin malah bersendau-gurau dengan temannya. Memang kurikulum terbaru mengharuskan pengajaran diberikan dengan cara siswa aktif. Tapi, bagaimana pelaksanaan di lapangan? Apalagi ketika ulangan atau ujian materi soal lebih banyak text book.
Pengganti istilah pelajar/siswa/murid menjadi peserta didik sebenarnya makin mempertegas murid “harus” dalam posisi pasif, gurunya yang aktif. Dari arti kata, “peserta” bermakna ikut serta untuk suatu kegiatan. “Ikut serta” itu sangat tergantung kepada yang diikuti, artinya pasif. Seaktif-aktifnya “peserta” tetap sangat tergantung kepada yang “diikuti”, yaitu guru.
Berharap negara, dalam hal ini kementrian pendidikan, mampu menciptakan generasi yang melek baca bisa memerlukan waktu lama dan butuh kesabaran ekstra dalam masa penantian. Karena tahapannya terlalu panjang, rantainya berliku. Apalagi jika menyangkut anggaran negara yang sangat prosedural proses pencairannya.
Maka, berharap pada lembaga pendidikan swasta seperti Muhammadiyah adalah pilihan lain yang mendekatkan kepada solusi. Mau tidak mau penyelenggaraan pendidikan formal tetap mengacu kepada kurikulum yang dikeluarkan kementrian. Tetapi dalam prosesnya lembaga swasta bisa mengkreasi agar siswanya benar-benar bisa aktif. Hal ini tidak hanya memerlukan guru “cerdas”, tetapi harus didukung oleh lingkungan pendidikan dan berbagai fasilitas, juga komunikasi dengan keluarga siswa.
Siswa aktif antara lain terlihat pada munculnya kesadaran (berawal dari sebuah kewajiban) mencari sendiri materi pembelajaran. Materi-materi tersebut kemudian dipahami sendiri, dengan bimbingan tutorial dari guru, jika memang benar-benar memerlukan. Membaca yang tadinya merupakan kewajiban, lambat laun berubah sebagai kebutuhan.
Menurut penulis, disinilah terjadi sebab awal rendahnya budaya membaca pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Mereka lebih banyak “dijejali” tanpa bisa menolak. Rejim penjajah Belanda sangat suka dengan cara-cara seperti itu tujuannya untuk mempertahankan kekuasaan di bumi Nusantara. Bagi penjajah “orang Indonesia tidak boleh cerdas.”
Menumbuhkan budaya literasi tidak bisa diselesaikan satu kelompok atau komunitas. Hal ini memerlukan kerja bareng, bergandengan tangan, termasuk dengan pengambil kebijakan dan keputusan dalam dunia pendidikan formal. (*)
Heru Prasetya
anggota Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PWM DIY. Pernah menjadi wartawan di beberapa media cetak.
Tags: MenumbuhkanBudayaLiterasi , KopdarnasPenggiatLiterasi , HeruPrasetya