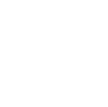Menyongsong Kopdarnas Literasi: MEMULAI AKTIVISME LITERASI DI RBK
Dibaca: 1430
Penulis : Alhafiz Atsari

Sedari SMA saya tidak pernah melakukan aksi-aksi dalam komunitas apapun termasuk komunitas literasi. Kecanggungan itu hadir ketika saya hijrah ke Yogyakarta dan berjumpa dengan sekelompok orang yang melibatkan diri di sebuah rumah baca.
Menghabiskan waktu dengan mengantarkan buku, meminjamkan ke masyarakat di Kota Yogyakarta, dan mendonasikan buku-buku mereka ke rumah baca. Ini adalah momen dimana saya pertama kali melihat orang-orang yang hidupnya berjibaku dengan buku.
Yang ada dipikiran saya ketika itu, ‘kurang kerjaan, orang saja beli buku mikir-mikir, harus nabung, puasa, dan makan ala kadarnya, ini kok malah disumbangin’. Kadang-kadang, kita juga sulit untuk merogoh kocek jika buku itu mahal bagi kita, misalnya saja ‘100 ribu lebih, bagi saya ketika itu, mendonasikan buku dengan harga segitu adalah hal konyol’.
Kecenderungan seseorang untuk terlibat sebagai pegiat literasi biasanya dimulai setelah ia memasuki jenjang studi di perguruan tinggi setempat. Namun, pernyataan ini tidak bisa dijadikan sebuah patokan mutlak. Tidak semua mahasiswa kelak akan menjadi seorang aktivis literasi. Kecanggungan dan keengganan menjadi salah satu penyebab yang lumrah terjadi.
Keenganan untuk melakukan aktivitas ini biasanya dilatarbelakangi oleh tidak adanya motivasi ketika mereka duduk dijenjang SMA. Motivasi sebagai seorang mahasiswa masih dijajali dengan cara berpikir ‘melanjutkan ke jenjang kuliah itu penting, penting untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan jangan berpikir yang aneh-aneh, buang-buang uang dan waktu untuk berorganisasi atau berkomunitas’. Cara-cara berpikir seperti ini pun masih dengan mudah ditemui dan diamini oleh para pengajar di perguruan tinggi, termasuk di kampus saya ketika itu.
Masa peralihan siswa ke mahasiswa menjadi sebuah proses yang sulit jika ia masih belum menemukan jalan yang benar, apalagi untuk menjadi seorang aktivis literasi. Saya mengawali perkenalan dengan dunia ini ketika masih menjadi seorang mahasiswa semester tiga.
Kala itu, saya mendapatkan seorang dosen yang cukup membosankan ketika mengajar. Kehadirannya selalu diiringi dengan tugas yang tiada henti-hentinya. Dengan ketidaktahuan akan latar belakangnya dan sikap acuh saya sebagai mahasiswa. Bapak itu mengajak kami untuk mendiskusikan tugas mini riset di sebuah tempat, sebut saja Rumah Baca Komunitas (RBK).
Jadwal pertemuan disepakati, akhirnya saya datang sendiri ke RBK. Kesan pertama saya ketika sampai adalah sebuah ketidaktertarikan ‘cat temboknya pudar, terletak di ujung jalan buntu, dan dikelilingi rumah-rumah dari kelas menengah bawah’. Tidak ada yang istimewa jika saya perhatikan dari luar rumah. Keadaannya begitu berbeda dengan perumahan yang terletak kurang lebih 150 meter dari rumah ini.
Untuk mencapai rumah ini, harus melalui jalan menurun, melewati jalan yang tidak diaspal, begitu kontras dengan perumahan yang berada di atas, jurang ekonomi yang begitu kentara. Bagi saya ketika itu, ini bukanlah hal menarik dan mengusik pikiran saya yang dipenuhi ‘kamu adalah mahasiswa, kamu harus hidup di tempat yang layak, dan tidak akan melakukan aktivisme literasi seperti itu dan di tempat itu.
Ruangan dalam berisi tumpukan buku yang disusun di rak kayu sederhana seperti rak buku yang biasa dijumpai di indekos mahasiswa Jogja. Saya dipersilahkan masuk oleh salah satu pegiatnya. Sialnya, dosen yang ditunggu belum kunjung datang ‘dan memang pada akhirnya tidak datang’.
Sembari menunggu, ada seorang pegiat yang menemani saya. Tidak ada percakapan yang begitu berarti saat itu, belum ada ilham untuk menggali lebih jauh tentang komunitas ini. Bagi saya saat itu, saya merasa canggung berada di tempat seperti itu. Saya tidak memiliki pengalaman tentang aktivitas seperti ini, bahkan ini pertama kalinya saya melihat sebuah taman baca atau rumah baca atau mungkin sebagian orang menyebutnya perpustakaan desa.
Saya terpikir untuk mencari buku yang bisa dijadikan bahan bacaan untuk riset saya. Tanpa saya duga, pegiat tersebut membantu saya mencari buku dan dengan ramah sekali mondar-mandir ke rak demi rak untuk mencari buku yang saya inginkan.‘maaf merepotkan mas’, ucap saya. Senyuman dan tetap melanjutkan pencarian buku lah yang saya terima dari respon pegiat itu. Ini sangat berbeda dengan suasana perpustakaan kampus, dimana para pustakawannya sangat tidak ramah dan ah sudahlah…
Ini sebuah perkenalan yang baik menurut saya ketika itu. Saya pulang dengan membawa buku. Beberapa hari kemudian, saya diajak oleh dosen saya untuk mengikuti diskusi di RBK. Diskusi berjalan seperti biasa. Saya menghadiri diskusi setiap hari rabu dan jum’at ditemani gorengan, jajanan dan kopi. Kehadiran saya dan teman-teman yang lain selalu diapresiasi oleh seluruh pegiat, kehangatan tanpa mengenal senior dan junior saya rasakan sedari awal. Aktivitas-aktivitas ini yang kelak akan menyeret saya dan mulai aktif sebagai pegiat literasi.

Sejak saat itu, saya juga dianggap sebagai seorang pegiat RBK. Lantas saya harus berbuat apa?. Saya tidak tahu mekanisme kerjanya. Saya rasa para pegiat RBK itu terlalu mudah memberikan rasa percaya kepada seseorang. Mungkin ini yang membuat RBK mampu melepas kecanggungan dan pengenalan aktivisme literasi.
Kecanggungan yang di awal saya miliki mulai terkikis dan penemuan jawaban atas aktivisme ini dimulai. Saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang fasilitator, bukan hanya memandu diskusi tapi juga sebagai pemateri. Rasa kekeluargaan dan semangat untuk berbagi ilmu dan buku kepada siapapun terpampang jelas di segala aktivitas RBK. Hari minggu yang biasanya digunakan oleh sebagian besar mahasiswa seperti saya untuk tidur, diganti dengan membawa buku ke Alun-alun kidul. Menggelar lapak buku, menunggu para pembaca hadir, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa.
RBK mengubah cara berpikir dan bertindak saya. Yang awalnya canggung, sekarang saya diajak untuk berpikir bebas dan mendalam. Mengenalkan buku, novel yang tidak pernah saya baca semasa SMA dan pikirkan selama ini, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya.
Setelah tiga tahun lebih bergiat di komunitas ini, melakukan aktivitas membaca, menulis dan menanam, RBK mengajarkan saya, mengapa para pegiat mau mengeluarkan duitnya untuk membeli jajanan saat diskusi? Mengapa mereka mau patungan, bantingan untuk membiayai komunitas ini agar tetap berjalan? Mengapa tidak mencari sponsor atau membuat proposal ke pemerintah?. Jawabannya sederhana, karena setiap orang bisa memulai aktivisme literasi dari dirinya sendiri seperti yang dilakukan Mbah Dauzan Farook.

Catatan Redaksi:
Judul asli dari penulis: Kecanggungan Memulai Aktivisme Literasi: Sebuah Refleksi
Tags: MemulaiAktivismeLiterasi , KopdarnasPenggiatLiterasi , AlhafizAtsari