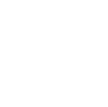Fenomena Disrupsi di Zaman Kolonial
.: Home > Artikel >
Majelis
02 September 2019 04:03 WIB
Dibaca: 1715
Penulis : Mu’arif*
Tags: FenomenaDisrupsidiZamanKolonial
Dibaca: 1715
Penulis : Mu’arif*
.jpg)
Awal-awal abad Kebangkitan Nasional—dalam perspektif sejarah Revolusi Industri—adalah abad Revolusi Industri 2.0 dengan ciri-ciri penemuan penting (discovery): “listrik” dan “mesin cetak.” Dua temuan besar inilah yang telah mengubah sejarah peradaban umat manusia: mengubah pola pikir, perilaku, tradisi, struktur sosial, dan pola relasi antar kelompok manusia. Dengan perspektif ini, sejarah awal kebangkitan nasional di Indonesia (Hindia-Belanda)—tanpa mengabaikan faktor Politik Etis—dapat diletakkan dalam konteks perubahan zaman yang diakibatkan oleh Revolusi Industri 2.0, yaitu dengan menjamurnya media-media massa—baik yang diinisiasi kaum pribumi maupun bangsa asing—pada tahun-tahun yang disebut dengan “zaman bergerak”—meminjam istilah Takashi Shiraishi (2005). Tengara ‘zaman bergerak’ bukan sekedar munculnya media-media massa nasional dalam skala massif, tetapi juga sekaligus menunjukkan proses transformasi mendalam gerakan kebangkitan nasional lewat organisasi-organisasi bumiputra yang mengusung ‘kesadaran berbangsa dan bernegara’ (nation-state). Sebelum sampai pada fase membangun ‘kesadaran berbangsa dan bernegara,’ apa yang terjadi pada masyarakat bumiputra adalah gejala yang saat ini disebut dengan istilah disrupsi seiring perubahan mode of culturedari masyarakat tradisionalis menuju masyarakat modern.
Media Sosial: Koran, Majalah, Almanak
Produk mesin cetak dalam bentuk media massa berfungsi sebagai media sosial yang efektif pada awal abad 20 atau tahapan awal Revolusi Industri 2.0. Kehadirannya mengiringi pertumbuhan gerakan-gerakan nasionalis bumiputra. ”Zaman bergerak” (1912-1926) adalah masa-masa peralihan model perjuangan kaum bumiputra dari yang sebelumnya cenderung fisik tetapi sporadis menjadi model perjuangan diplomasi secara kolektif. Faktor kebijakan politik etis memang tidak dapat diabaikan, seperti ungkapan Robert van Niel (2009: 102), “Mendidik massa besar bangsa Indonesia adalah juga bagian yang pokok dari politik etis kolonial dengan pemberantasan buta huruf dan menaikkan kemakmuran sebagai tujuan utama.”Ya, politik etis di bidang pendidikan memang telah melahirkan kelas elite modern yang melek literasi di tanah air pada waktu itu. Mereka adalah para lulusan sekolah-sekolah Belanda yang mengalami proses penyadaran lewat proses transmisi pengetahuan dari Barat. Lewat Pendidikan formal mereka mengenal teori-teori kehidupan berbangsa dan bernegara secara modern. Tetapi di luar faktor politik etis, sebenarnya kehadiran budaya baru yang datang dari Eropa—lewat kolonialisme Belanda—telah mengenalkan alat produksi modern bernama mesin cetak. Produk mesin cetak berupa media massa hadir secara massif. Dari sinilah sebenarnya kesadaran berbangsa dibangun lewat tulisan-tulisan menggugah nurani bangsa. Lewat media massa mereka membaca dinamika pemikiran liberal yang sedang bergulir di negara-negara Eropa.
‘Sang pemula’ yang mengawali gerakan baru ini, seperti dalam film Bumi Manusia, disebut Minke. Tetapi sebenarnya sosok Minke adalah representasi historis dari tokoh Tirto Adhi Soerjo, sang inisiator dan perintis media cetak kategori harian pertama dari kalangan bumiputra. Media yang ia rintis pertama kali pada tahun 1903 bernama Soenda-Berita, sebuah mingguan (semacam tabloid) yang dicetak di Cianjur. Pada tahun 1907, dia mendirikan mingguan Medan-Prijaji di Batavia yang tiga tahun kemudian (1910) berubah menjadi harian (koran) pertama yang dikelola oleh kaum bumiputra.Transformasi Medan-Prijaji dari mingguan hingga menjadi harian adalah suatu prestasi tersendiri bagi kaum bumiputra dalam industri media massa. Terbit tiap hari Sabtu, Medan-Prijaji mengusung motto: “Soeara bagai sekalian radja-radja, bangsawan asali dan fikiran, prijaji dan saudagar boemipoetra dan officer-officer serta saudara-saudara dari bangsa jang terprentah lainnja jang dipersamakan dengan anaknegri, di seluruh Hindia Olanda.” Selain menginisiasi terbitnya koran Medan-Prijaji,Tirto juga turut membidani lahirnya surat kabar yang dikelola oleh para intelektual bumiputra dari kalangan perempuan, yaitu Puteri-Hindia(1909). Adapun motto yang digunakan sebagai berikut: ”Seorat kabar dan advertentie boeat istri-Hindia.”
Surat kabar rintisan Tirto Adhi Soerjo harus bersaing dengan surat kabar lain yang lebih besar dan memiliki jaringan distribusi yang luas. Ketika Soenda Beritadan Medan-Prijajiterbit, keduanya harus bersaing dengan media massa yang diterbitkan oleh orang-orang Belanda dan China. Beberapa media massa kategori koran terbitan bangsa Belanda, seperti de Locomotif, Bintang Hindia, Surabajaasch Handelsblad, Java Bode, Het Nieuws van de Dag, dan lain-lain. Hampir sebagian besar koran yang terbit pada waktu itu memang dimonopoli oleh bangsa Belanda. Sedangkan surat kabar China yang termasuk kategori koran, seperti Li Po, Bintang Soerabaja, Sin Po, dan lain-lain.
Walaupun dilihat dari motto penerbitan Medan-Prijajimasih terkesan elitis, tetapi langkah Tirto Adhi Soerjo ini telah mengawali gerakan baru bagi kaum bumiputra. Seiring dengan lahirnya Boedi Oetomo (BO), organisasi ini juga menerbitkan media massa dengan durasi penerbitan yang lebih lama (bulanan), yakni Boedi Oetomo(1920). Selain Boedi Oetomo, sebuah surat kabar di Yogyakarta yang berafiliasi ke organisasi ini bernama Ratna Doemilah(1910), terbit seminggu dua kali. Sang pengemudi redaksi adalah tokoh yang turut membidani BO, yaitu Wahidin Soedirohoesodo.
Sangat menarik dalam hal ini bahwa pola penerbitan media massa sebelum memasuki ”zaman bergerak” menunjukkan pada model stratifikasi bisnis dari model: 1) harian (koran), 2) mingguan (tabloid, majalah), 3) bulanan (majalah), 4) hingga tiga bulanan atau enam bulanan, bahkan tahunan (almanak, berita tahunan). Kategori pertama adalah pola penerbitan yang paling prestisius karena memang harus ditopang dengan sistem kapital dan sumber daya manusia yang cukup. Kategori ini banyak dimonopoli oleh bangsa Belanda. Kategori kedua dan ketiga menjadi pilihan populer bagi gerakan-gerakan nasional yang sedang tumbuh di tanah air. Sedangkan kategori keempat menjadi pilihan terakhir gerakan-gerakan nasional yang menerbitkan ”berita tahunan” atau almanak untuk tujuan reportase perkembangan organisasi dalam kurun setahun.
Sejak memasuki tahun-tahun kebangkitan nasional, pilihan menerbitkan media massa kategori majalah memang sudah menjadi fakta populer. Faktor biaya produksi dan sumber daya manusia di bidang jurnalistik yang masih terbatas menyebabkan pola penerbitan media massa dengan durasi bulanan menjadi pilihan yang strategi bagi gerakan-gerakan bumiputra. Contoh yang paling mudah selain Boedi Oetomo adalah majalah Bintang Islam (terbit pertama kali 1923) dan Soewara Moehammadijah (terbit pertama kali 1915). Sedangkan produk cetak di bidang jurnalistik yang juga populer selain majalah (bulanan) adalah Almanakyang durasi penerbitannnya bisa sampai enam bulan atau bahkan tahunan. Untuk produk jurnalistik durasi tahunan kemudian dikenal dengan nama Berita Tahunan. Contohnya adalah Almanak Buning (Grup Djawi Kondo) dan Berita Tahoenan Moehammadijah Hindia Timoer (1927).
Hasil riset Abdurrahman Surjomijarjo (2008: 267-269, 243-248) paling tidak menyebut sekitar 60 media massa nasional yang dikelola secara profit oleh kaum bumiputra pada sekitar tahun sebelum 1930-an. Sedangkan surat kabar atau media massa yang dikelola secara profit di Yogyakarta mencapai 40-an media. Belum lagi media-media massa milik perkumpulan-perkumpulan lokal yang dikelola secara sederhana, dengan mekanisme penerbitan yang tidak teratur, serta jumlah oplag media yang sangat terbatas. Merebaknya pertumbuhan media-media massa pada masa kolonial seperti yang diungkapkan Tirto Adhi Soerjo dalam artikel, “Doenia Soerat-soerat Kabar Boemipoetra,” sebagai berikut: ”Adapoen perboeatannja soerat-soerat kabar Boemipoetera di poelaoe Djawa, begitoe djuga di loear djajahan, dan soerat-soerat kabar Tjina dan Melajoe, di dalam beberapa tahoen jang laloe ini soedah mendjadi sebagai tjendawan jang timboel dari tanah…”(Lihat Muhidin M. Dahlan & Iswara N. Raditya (ed.), Tirto Adhi Soerjo: Karya-karya Lengkap. Jakarta, Iboekoe, 2008).
Disrupsi
Menjamurnya media massa pada zaman kolonial bagai “tjendawan jang timboel dari tanah”—meminjam istilah Tirto Adhi Soerjo, telah mengubah pola pikir, perilaku, tradisi, struktur sosial, dan pola relasi antar kelompok dalam struktur masyarakat kolonial. Perubahan yang cepat dan massif di satu sisi memang menguntungkan bagi percepatan pembentukan kesadaran nasionalisme di tanah air, tetapi di sisi lain justru banyak kalangan yang dirugikan. Pertama, dengan kemudahan akses informasi dan pengetahuan, maka jasa pengantar informasi (kurir) di zaman kolonial telah bergeser menjadi tukang loper koran atau malah hilang sama sekali. Dengan terbukannya jalur transmisi keilmuan, kaum intelektual bumiputra semakin mudah mengakses pengetahuan-pengetahuan baru dari Barat. Akses terhadap pengetahuan dari Barat inilah yang menjadi babakan awal munculnya kesadaran nasionalisme baru di tanah air.
Kedua, mesin cetak yang mampu memproduksi barang cetakan secara massal telah mengilangkan profesi juru tulis atau jasa penyalin kitab-kitab klasik. Gejala disrupsi yang paling kentara di kalangan umat Islam tradisionalis, karena otoritas pengetahuan dan sumber belajar sudah tidak dimonopoli oleh figur-figur kharismatik di pondok pesantren (para kyai) dengan hadirnya buku-buku cetak keagamaan. Bagi kelompok Islam yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman ini, secara otomatis model-model dan metode-metode belajar mengalami perubahan secara drastis menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern.
Ketiga, media massa cetak tidak hanya menyajikan informasi (lewat sajian news) dan pengetahuan (lewat sajian artikel), tetapi juga sekaligus memuat advertensi (iklan) produk-produk bernilai ekonomis. Dengan demikian, seiring menjamurnya media massa, pergerakan ekonomi kaum bumiputra turut terdongkrak dengan hadirnya ruang-ruang periklanan berbasis media massa. Maka model promosi produk-produk tidak lagi dilakukan secara tradisional, tetapi sudah modern menggunakan kepiawaian seni mendesain gambar dan merangkai kata-kata persuasif di media massa. Produk industri batik, baik di Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, dan Batavia membanjiri ruang-ruang advertensi di media-media massa pada waktu itu.
Keempat, hadirnya media massa secara tidak langsung telah memangkas jarak atau durasi proses pertukaran informasi—dalam beberapa kasus orgaan pergerakan disebut ‘koordinasi’—sehingga mengubah pola kohesi dalam masyarakat. Jika ditengarai secara seksama, hampir setiap organisasi pergerakan memiliki corong media massa tersendiri. Selain sebagai alat perjuangan, media massa berfungsi sebagai alat koordinasi antara pusat dan daerah sehingga proses pergerakan lebih mudah dan cepat. Secara otomatis, teori jurnalistik yang berkembang pada waktu itu belum mengenal teori jurnalisme yang independent karena setiap media massa adalah alat atau corong pergerakan dari suatu organisasi.
Itulah fenomena disrupsi pada zaman kolonial, khususnya memasuki tahun-tahun yang oleh Takashi Shiraishi disebut sebagai ‘zaman bergerak.’ Yaitu, suatu zaman yang paling dinamis (aktif dan reaktif) sebagai dampak dari menjamurnya media massa di tanah air. Kehadiran media massa yang begitu massif telah mengubah pola pikir, perilaku, tradisi, struktur sosial, dan pola relasi antar kelompok mengisyaratkan suatu peralihan mode of culture, dari masyarakat tradisionalis menuju masyarakat modernis. Keberhasilan suatu kelompok masyarakat dalam menghadapi era disrupsi adalah bagaimana sikap dan responnya terhadap tantangan zaman. Bagi yang mampu beradaptasi dengan zaman, maka mereka telah berhasil menjinakkan disrupsi dan menjadi pemenang. Tetapi bagi mereka yang menutup diri, tidak mampu beradaptasi dengan zaman, maka mereka mengalami kerugian besar dan selanjutnya hanya menjadi penonton di pinggiran.
Memasuki awal abad 21, ‘goncangan’ (disrupsi) kembali terulang ketika hadirnya penemuan internet dan aplikasi jejaring sosial berbasis online. Memasuki era Revolusi Industri 4.0, zaman kembali dinamis (aktif dan reaktif) sehingga menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, pola disrupsi tidak jauh berbeda dengan saat ini. Jika pada awal abad 20 teknologi informasi yang mengguncang peradaban manusia dalam bentuk media cetak, kini teknologi informasi yang hadir berbasis online. Maka bagi siapa saja yang mampu beradaptasi dengan teknologi informasi berbasis internet, dia akan mampu menjinakkan disrupsi dan akan keluar sebagai pemenang. Sebaliknya, siapa yang menutup diri, tidak mampu beradaptasi dengan teknologi mutakhir, maka dia akan mengalami kerugian besar dan hanya menjadi penonton di pinggiran. []
*) Pengkaji sejarah Muhammadiyah-‘Aisyiyah, Anggota MPI PP Muhammadiyah
sumber: pustakamu.id
Tags: FenomenaDisrupsidiZamanKolonial